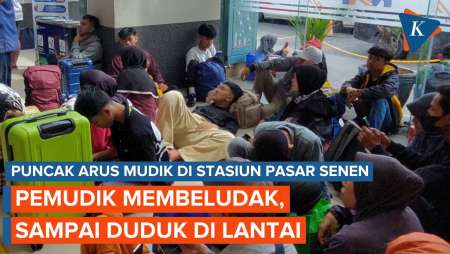Ke Mana Kita? #kaburajadulu
Oleh: Nugroho Iman, Jurnalis Kompas TV, Dosen Komunikasi, dan Alumni Kriminologi
Ketika saya sedang scrolling instagram, saya berhenti sejenak untuk menyimak sebuah unggahan dari Prof Rhenald Kasali di laman berikut ini https://www.instagram.com/p/DF6kUQ3SwMG/
Baca Juga: Lansia dan Ancaman Korban Kejahatan Teknologi
Dalam postingan di laman itu Rhenald Kasali menuliskan pada ruang caption-nya;
“Baru-baru ini ramai menjadi perbincangan #kaburajadulu yang berisi ajakan untuk masyarakat untuk kabur dari Indonesia sebagai bentuk kekecewaan pada kondisi saat ini. Hal ini sejalan dengan fenomena brain drain yang terjadi pada banyak SDM berkualitas Indonesia yang pindah kewarganegaraan salah satunya ke Singapura.
Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian dengan kondisi negeri kita saat ini? #stayrelevant “.
Dari unggahan tersebut, Rhenald Kasali menangkap fenomena dan menjelaskannya dari perspektif bisnis serta manajemen untuk tetap relevan.
Saya juga mengikuti tagar #kaburajadulu yang sempat viral di platform X dan menyebar ke berbagai platform media sosial lainnya.
Tagar itu masih menjadi pembicaraan informal di ruang publik hingga saat ini.
Apa yang dikatakan Rhenald Kasali itu seketika mengusik saya juga, apalagi di masa seperti ini. Kira-kira apa saja yang menyebabkan tagar itu muncul?
Baca Juga: Urbi Et Orbi
Ada Lapangan Kerja? Ada, tapi…
Data BPS (Badan Pusat Statistik) 2024 menyebutkan, mayoritas penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal.
Pada Agustus 2024 lalu, setidaknya ada 83 juta jiwa lebih atau sekitar hampir 58% pekerja yang bekerja di sektor informal.
Sedangkan yang bekerja di sektor formal tercatat hampir 61 juta jiwa atau setara 42%.
Dari angka-angka itu kita bisa melihat sebuah fenomena, pemerintah belum cukup mampu menyediakan lapangan kerja formal untuk menyerap lulusan perguruan tinggi masuk ke industri formal.
Sisanya terserap di industri non formal. Seperti berdagang, wirasawasta, pekerja lepas dan sebagainya.
Meskipun pemerintah sampai kini masih terus berupaya menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan dunia pendidikan, tetapi hasilnya di lapangan belum terlihat nyata.
Terlebih, para penyedia lapangan kerja di industri formal yang terkendala banyak hal. Seperti faktor birokrasi perizinan, hingga gangguan keamanan dari beberapa oknum ormas.
Ini juga yang memunculkan fenomena brain drain, sebuah fenomena di mana warga terdidik memilih ke luar negeri atau ke luar negara mereka untuk mencari kerja.
Istilah brain drain awalnya digunakan oleh British Royal Society di tahun 50-60-an.
Untuk menggambarkan banyaknya orang pintar Inggris yang “merantau” ke negara lain, seperti Amerika Serikat.
Karena menganggap kehidupan di Amerika lebih baik daripada di negeri mereka sendiri.
Belakangan, kini fenomena itu muncul di Indonesia melalui tagar #kaburajadulu.
Bagi para gen Z yang notabene lulusan perguruan tinggi, mereka pintar, memiliki daya kritis, terkoneksi secara global melalui sosial media, dan outspoken (blak-blakan) ketika melihat situasi dan kondisi Indonesia, khususnya saat ini.
Anak Muda Resah
Anak muda saat ini resah dan gelisah karena melihat situasi negara yang dicintai sepertinya tidak memberikan optimisme bagi mereka.
Terkhusus bagi para gen Z yang baru akan masuk dan mulai menapaki dunia kerja.
Apalagi mencuat peristiwa di tengah efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah, salah satu kementerian malah mengangkat staf khusus (stafsus).
Meskipun hal tersebut dibolehkan menurut aturan, tetapi ini seperti melukai mereka.
Perdebatan mengemuka di media sosial pada kolom komentar postingan yang menginformasikan mengenai hal tersebut.
Misalnya berdebat mengenai gaji diterima stafsus yang dibandingkan dengan pegawai honorer yang kehilangan pekerjaan.
Atau perdebatan mengenai apa tugas stafsus dibandingkan dengan pekerjaan guru.
Atau seorang stafsus dari kalangan pesohor yang selalu hadir dalam acara-acara diskusi, seremoni yang seolah tidak terlihat kerja nyatanya.
Fakta-fakta kontradiktif tersebut menjadi pencetus bagi gen Z untuk bersuara melalui tagar.
Silent majority yang melihat situasi di negaranya yang tidak sesuai harapan mereka dan bahkan membawa pesimisme.
Belum lagi masalah kenaikan harga barang, kelangkaan bahan kebutuhan seperti gas, serta pajak yang menghimpit kehidupan mereka.
Bagi saya, tagar #kaburajadulu menjadi fenomena baru di generasi Gen Z, khususnya di kelas menengah.
Mereka ingin memiliki kehidupan pribadi, ekonomi, dan yang lebih baik karena mereka melihat kesempatan itu sulit didapatkan di Indonesia.
Mereka bukan tidak mencintai Indonesia, tetapi dengan merantau ke luar negeri mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dibanding di dalam negeri.
#kaburajadulu dan VUCA
Hidup pascapandemi Covid 19 membawa perubahan revolusioner bagi gen Z.
Hal itu setidaknya bisa disimak ketika merujuk kepada VUCA 5.0 (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Inilah konsep dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi yang dipopulerkan Burt Banus pada kisaran 1987 silam.
Kita coba lihat satu persatu secara sederhana, apa saja tantangan generasi Z jika merujuk ke VUCA dan situasi saat ini.
Pertama, Volatility atau perubahan yang cepat dan tidak terduga. Era teknologi disadari menggerus sejumlah industri dan pekerjaan sekaligus.
Pekerjaan yang dulu dikerjakan manual atau analog, kini mulai digantikan sistem komputasi dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Bagi Gen Z, pekerjaan entry level seperti clerk atau customer service yang seharusnya menjadi tangga awal mereka meniti karir, kini bisa digantikan teknologi.
Padahal keahlian (skill) dan pengalaman seperti ini sangat mereka butuhkan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri, serta bergaul di dunia nyata.
Mereka berusaha berubah dan lentur dengan menguasai teknologi, tetapi lapangan kerjanya justru sebaliknya. Menyempit karena perubahan teknologi.
Volatilitas seperti ini menjadi tantangan sendiri bagi gen Z. Sehingga keinginan bekerja di luar negeri diharapkan bisa membuat mereka menambah pengalaman, memperluas wawasan kehidupan dan relasi demi kehidupan yang lebih baik. Walaupun pekerjaan itu menjadi waiter di luar negeri.
Konotasi V yang lain bisa berarti Vulnerability atau kerentanan. Dalam hal kerentanan ini ada dua macam. Pertama, kerentanan fisik. Kedua, kerentanan non fisik.
Kerentanan fisik terhadap penyakit yang disebabkan gaya hidup dan pola konsumsi juga menjadi tantangan di kalangan gen Z.
Terutama mereka yang hidup di perkotaan dengan gaya hidup sedentary, yakni kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur, dengan karakteristik keluaran kalori sangat sedikit.
Menumpuk timbunan lemak yang berasa dari gula yang tidak diolah tubuh menjadi energi sebagai akibat makanan kekinian yang banyak beredar.
Kemudian tantangan non fisiknya seperti banyak konten di media sosial mengenai lingkungan kerja yang makin kompetitif, dan tidak mendukung pengembangan pribadi (toxic environment), juga mempengaruhi mental psikologis.
Harapan mereka jika bekerja di luar negeri, para gen Z ini akan bisa hidup lebih sehat secara fisik dan mental.
Lalu mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakukan yang lebih fair dalam pekerjaan.
Selanjutnya yang kedua adalah Uncertainty atau ketidakpastian hidup.
Era teknologi dan informasi disadari mempengaruhi pemikiran mereka. Misalnya Informasi mengenai besarnya pungutan pajak yang rumit sulit dipahami mereka.
Lalu bagaimana mereka bekerja tanpa kejelasan karir dan masa kerja. Ditambah pengeluaran tak terduga yang mesti mereka hadapi ketika akan bekerja kelak.
Adapun yang ketiga adalah Complexity atau kompleksitas hidup.
BPS pada November 2024 mencatat, angka standar hidup layak yang representasi adalah pengeluaran per kapita di Indonesia.
Menurut BPS, seseorang itu akan mengeluarkan uang Rp12,34 juta per tahun.
Artinya, seorang member gen z akan mengeluarkan biaya Rp1 juta rupiah lebih per bulan untuk dapat hidup layak.
Sebuah kenyataan yang berat bagi para gen Z harus bisa memenuhi standar kebutuhan untuk diri dan keluarga.
Ditambah lagi isu-isu mengenai gen z yang sulit untuk memiliki hunian dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi pemicu mereka ingin pindah dan bekerja di luar negeri.
Harapanmya tentu mendapatkan penghasilan lebih besar, lebih baik, dan bisa membantu keluarga di tanah air.
Kemudian yang keempat adalah Ambiguity nilai dan norma yang berubah seiring perubahan waktu.
Kontradiksi antara nilai yang mereka dapatkan di rumah dan lingkungan ternyata berbeda dengan apa yang mereka hadapi di dunia nyata, atau setidaknya dari situasi yang mereka lihat dan dapatkan melalui media sosial.
Kata the power of ordal atau kekuatan “orang dalam” ketika mencari kerja juga menjadi kata yang populer dalam kolom komentar.
Mereka menganggap kalau mau mendapatkan kerja harus ada “orang dalam” supaya bisa diterima. Ini sebuah kontradiksi nilai bagi mereka.
Seseorang yang diterima bekerja seharusnya berdasarkan kompetensi dan bukan karena hasil nepotisme.
Padahal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah lama disepakati menjadi nilai dan norma yang tidak baik, dan telah menjadi nilai kehidupan mereka.
Tetapi prakteknya mereka melihat sebaliknya melalui media sosial. Mereka melihat maraknya kasus penyalahgunaan wewenang karena berkuasa.
Lalu kasus korupsi yang mereka konsumsi melalui media sosial dan lain sebagainya.
Dengan bekerja di luar negeri, mereka berharap tidak ada KKN dalam bekerja, dan seseorang dinilai dari kompetensi dan integritasnya.
Baca Juga: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Antara Harapan dan Realita Pahit
Akhirnya, tagar #kaburajadulu sebenarnya bukan sebuah statement bahwa gen z tidak nasionalis atau tidak cinta negara.
Tetapi ironi, kontradiksi atas banyak peristiwa di dalam negeri yang terjadi membuat mereka tipis harapan.
Ketidakadilan, lalu perbedaan ucapan dan perbuatan para pejabat membuat mereka merasa tidak terwakili.
Mereka berkaca terhadap diri mereka harus berubah, utamanya untuk bisa mendapatkan nafkah layak dan baik di negeri tercinta menipis.
Kesempatan itu ada jika mereka pergi ke luar negeri. Ada pula komentar netizen yang pernah saya baca berkaitan dengan ini.
Jangan sampai tagline Indonesia emas berubah Indonesia cemas, dan berakhir menjadi Indonesia lemas. Semoga tidak.

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
REKOMENDASI UNTUK ANDA
KOMPASTV SHORTS
BERITA LAINNYA
Warga Myanmar Gotong Royong Cari Korban Gempa, Kota Mandalay Dipenuhi Bau Mayat
30 Maret 2025, 23:00 WIBMuslim di Belanda Rayakan Idulfitri pada Minggu, Khatib Minta Umat Doakan Warga Gaza
30 Maret 2025, 22:50 WIBLink Live Streaming Inter Milan vs Udinese di Serie A, Kick-off Pukul 23.00 WIB
30 Maret 2025, 22:30 WIBTakbir Berkumandang, Bedug Ditabuh! Begini Suasana Malam Takbiran di Masjid Istiqlal Jakarta
30 Maret 2025, 22:27 WIBSemarak Warga Cirebon Pawai Obor dan Kumandangkan Takbir Sambut Hari Raya Idulfitri
30 Maret 2025, 22:21 WIBLengkap! Posko Mudik BSI di Pelabuhan Merak Siapkan Cek Kesehatan dan Kursi Pijat Gratis
30 Maret 2025, 22:18 WIB[FULL] Kesiapan Masjid Istiqlal Menyambut Idulfitri 2025, Imbau Warga Terkait Hal Ini
30 Maret 2025, 22:10 WIBSiswi 19 Tahun Jadi Tersangka Pembuang Bayi di Medan, Polisi Selidiki Dugaan Pencabulan
30 Maret 2025, 22:10 WIBFOLLOW US
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.










![[FULL] Pidato Surya Paloh di HUT ke-13 NasDem, Singgung Posisi Partai di Pemerintahan Prabowo](https://media-origin.kompas.tv/library/image/thumbnail/1731316292/DIT_-_PALOH_JANGAN_PERNAH_HILANGKAN_KOMITMEN___1731316292.png)















![[FULL] AHY Cek Kesiapan Mudik Lebaran di Pasar Senen, Lepas Keberangkatan Kereta](https://assets-studiohub.kompas.com/video2019/73f614858444241bddf143/5b73469e82c67f1e9d34d3d14c9bf215/t_5b73469e82c67f1e9d34d3d14c9bf215.jpg)